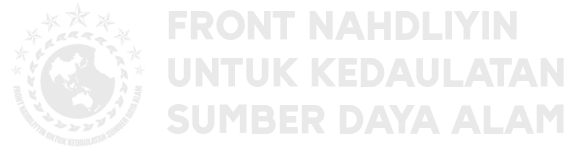Sebuah Pendahuluan: Menguji Klaim Baik BBM Naik
Oleh: Ahmad Syifa (anggota Biro Agitasi dan Propaganda)
Beberapa hari yang lalu harga BBM dinyatakan naik. Khususnya untuk pertalite, dari Rp7.600 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kenaikan itu karena subsidinya dikurangi Rp2400. Alasannya, subsidi untuk BBM ini terlalu besar, sehingga membebani APBN. Itupun tidak sepenuhnya, sebab pemerintah menyebut harga aslinya Rp14.000 per liter. Jadi pemerintah masih mensubsidi sebesar Rp4.000.
Sementara itu pemerintah menyebutkan bahwa selama ini 70% subsidi energi itu dinikmati oleh orang-orang mampu. Agar penyaluran subsidi itu tepat sasaran, pemerintah bermaksud mengalihkan subsidi BBM ke program bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial ini disalurkan untuk 20 juta orang lebih yang dianggap tidak mampu. Dengan begitu, pemerintah beranggapan masalah sudah selesai. Pemerintah seolah sudah cukup membayar kompensasi kenaikan BBM.
Akan tetapi jika dicermati, klaim-klaim itu mengandung banyak kejanggalan. Benarkah subsidi energi sangat membebani APBN? Benarkah selama ini 70% subsidi energi dinikmati oleh orang-orang yang mampu? Benarkah program kompensasi berupa bantuan sosial dapat meringankan beban rakyat miskin salah satunya akibat kenaikan harga BBM? Lebih jauh, mengapa pemerintah merasa subsidi energi sebagai beban untuk APBN?
Pertama, pemerintah selalu mengutarakan klaim bahwa APBN sangat terbebani oleh subsidi energi. Misalnya dengan menyampaikan bahwa harga asli pertalite adalah Rp14.000 per liter dan dijual dengan harga Rp7.600 per liter. Jadi subsidinya sebesar Rp6.400 per liter. Ini dianggap terlalu besar, dan akhirnya subsidinya dikurangi Rp2.600.
Seolah-olah pemerintah membuka data yang menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar terbebani. Masalahnya ketika pemerintah mengklaim terbebani oleh harga pertalite Rp7.600 per liter, pemerintah tidak pernah membuka data, berapa harga modalnya. Dari harga modal itulah rakyat akan percaya bahwa pemerintah memang benar terbebani.
Sudah sepatutnya rakyat berhak menuntut transparansi kinerja usaha BUMN, karena mereka dibiayai publik dan mengklaim sebagai sektor publik. Ataukah memang negara bermaksud mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat. Ataukah bunyi UUD Pasal 33 sudah berubah menjadi “…bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperdagangkan kepada rakyat?”
Kedua, pemerintah mengklaim 70% subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang yang mampu. Dari mana pemerintah mengambil angka 70% itu juga perlu dipertanyakan. Disebut bahwa orang yang mampu itu orang yang memiliki mobil pribadi. Maka jika begitu, jelas masalahnya adalah mereka mengambil jatah subsidi yang seharusnya untuk orang miskin.
Mestinya kebijakan yang dilakukan bukan mencabut subsidi BBM. Misalnya dengan pembatasan pembelian untuk “orang-orang yang mampu” entah dari volume ataupun jenisnya, atau bentuk batasan-batasan lainnya. Rakyat pun akan yakin jika benar pemerintah memiliki itikad dan kemauan politis yang baik, pemerintah akan mampu menemukan cara-cara lain yang kreatif yang tidak merugikan rakyat.
Di samping itu kebijakan yang mestinya lebih tepat dikeluarkan adalah kebijakan transportasi publik yang berpihak pada rakyat. Seperti tansportasi dengan ongkos yang terjangkau, dan dengan fasilitas yang memadai. Sehingga menjadi cukup alasan untuk lebih menggunakan transportasi publik.
Namun faktanya tidak begitu. Harga transportasi kian hari kian mahal. Bahkan justru salah satu dampak langsung dari kenaikan harga BBM ini adalah harga transportasi publik yang kian melambung dan tidak terjangkau. Logikanya justru akan berbalik dan menjadi alasan orang-orang untuk semakin meninggalkan transportasi publik.
Ketiga, pemerintah bermaksud menyalurkan bansos sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM sebagai solusi permasalahan rakyat. Padahal jumlah bansos itu sangat terbatas, dan waktunya sangat singkat. Hanya Rp600.000 per bulan, dalam 4 bulan. Logikanya semakin sulit diterima. Sebab, buntut dari kenaikan BBM adalah kenaikan di hampir semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rakyat.
Hitung-hitungan kasar saja, seumpama seseorang memiliki anak sekolah yang harus pulang pergi menggunakan angkutan umum. Sementara harga angkutan misalnya naik Rp2.000 rupiah sekali jalan. Maka pulang pergi tambahan ongkosnya Rp4000. Itu kalau satu kali naik angkutan. Kalau lebih, ongkosnya lebih mahal lagi. Jika dikalikan selama 30 hari sudah Rp120.000 per anak, per satu jenis transportasi.
Belum biaya transportasi untuk keperluan yang lain-lainnya, seperti pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga. Belum biaya untuk tambahan kenaikan bahan pangan, yang setiap item mengalami kenaikan. Jika pun rakyat terbantu oleh bansos, itu hanya berlangsung selama 4 bulan. Selebihnya, rakyat akan menanggung sendiri kesulitan yang dihadapi akibat kebijakan kenaikan harga BBM.
Keempat, klaim pemerintah bahwa APBN terbebani oleh besarnya subsidi energi. Padahal jelas energi adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Subsidi energi bukan sekedar besaran angka-angka beban negara, melainkan salah satu tanggung jawab utama pemerintah kepada rakyatnya. Juga menjadi cerminan dan tolak ukur berhasil atau gagalnya sebuah negara mengurus urusan warganya.
Disamping itu ketika pemerintah mengklaim subsidi energi sebagai beban APBN, mengapa proyek-proyek yang tidak dibutuhkan oleh rakyat terus dijalankan? Sebut saja pembangunan ibu kota baru, bandara, jalan tol dan banyak proyek nasional lain yang diklaim strategis tapi sama sekali tak strategis bagi rakyat, bahkan justru seringkali mengorbankan rakyat. Mengapa bukan anggaran itu saja yang dipangkas atau kalau perlu dicabut saja sekalian?
Belum lagi, banyak kasus-kasus korupsi sudah lama tak diselesaikan. Sebut saja kerugian negara yang disebabkan korupsi sumber daya alam mencapai puluhan trilliyun per tahun. Catatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK (GNPSDA-KPK) pada 2018 menyebutkan, kontribusi pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya 99,91 triliun atau 3,87 persen. Padahal mestinya jauh lebih besar dari itu.
Misalnya, PNBP sektor kelautan 70 triliun per tahun namun hanya diperoleh 230 miliar per tahun. Potensi pendapatan sawit di 2018 diketahui mencapai 40 triliun namun pajak terpungut hanya mencapai 21,87 triliun. Kemudian di sektor minerba, potensi kerugian negara akibat kurang bayar pajak sebesar 15,9 triliun dan akibat administrasi serta perizinan yang buruk mencapai 28,5 triliun. Itu belum semua, masih banyak di sektor-sektor lainnya.
Dari situ rakyat mestinya berhak bertanya, mengapa pemerintah tidak menyelesaikan masalah-masalah itu saja? Mengapa kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi rakyat menjadi solusi andalan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran APBN? Mengapa pemerintah harus membebankan masalah yang justru menjadi tanggung jawabnya selalu kepada rakyat?
Sampai di sini semakin membuktikan bahwa masalah kenaikan BBM bukan sekedar pertimbangan angka-angka fiskal yang netral, melainkan soal titik pijak di mana negara ini berpihak.