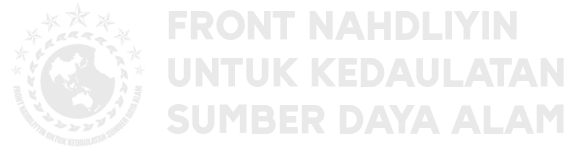Katakan Saja Kebijakan Agraria, Bukan Reforma Agraria
Roy Murtadho (Koordinator Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam/FNKSDA, & Peneliti Sajogyo Institute Bogor)

“Kebijakan Reforma Agraria Jokowi bukanlah Reforma Agraria (genuine). Jadi, tak ada Reforma Agraria, yang ada hanyalah kebijakan agraria. Karena itu jangan menyebut kebijakan agraria Jokowi sebagai Reforma Agraria. Ini menyesatkan. Land Reform saja bukan, apalagi Agrarian reform.” Demikian pernyataan Gunawan Wiradi, pemikir agraria kenamaan, yang disampaikan berulangkali dalam berbagai kesempatan diskusi mengenai Reforma Agraria.
Tidak bisa dipungkiri, kini terminologi RA telah menjadi pembicaraan hangat tak hanya di kalangan para penstudi dan pegiat agraria, tapi juga di masyarakat luas, setelah diadopsinya terminologi RA ke dalam nomenklatur kebijakan agraria di era pemerintahan Jokowi. Di kalangan para penstudi dan pegiat agraria sendiri, sejak semula telah terjadi perdebatan yang cukup keras, ada yang menganggapnya sebagai berkah, namun ada pula yang menganggapnya sebagai musibah.
Pihak pertama melihat pengadopsian terminologi RA ke dalam kebijakan pertanahan pemerintah sebagai langkah maju, setelah sekian lama RA gagal dilaksanakan di Indonesia. Mereka melihatnya sebagai kesempatan politik yang harus didukung, seartifisal apapun pelaksanaannya. Sementara bagi pihak kedua melihatnya sebagai upaya pereduksian pengertian RA yang (genuine).
Di mana alih-alih menjawab persoalan ketimpangan struktur agraria dan konflik di sektor agraria, pelaksanaannya yang artifisial justru memberi peluang penguasaan tanah untuk kepentingan modal melalui sertifikasi tanah. Belakangan perdebatan berlangsung dalam suasana makin gaduh setelah presiden Jokowi menyebut data penguasaan lahan Prabowo di Kalimantan dan Aceh, pada debat calon presiden putaran kedua beberapa waktu lalu.
Di sinilah letak persoalannya. Perlu adanya pendiskusian kebijakan agraria dengan kembali merujuk pada semangat serta tujuan RA di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang kerap disebut RA Sejati. Apalagi terdapat banyak kejanggalan dalam pelaksanannnya. Apakah tepat kebijakan agraria Jokowi disebut RA?
Reforma Agraria Sejati
Reforma Agraria yang sejati (genuine) sekurangnya mempunyai tiga ciri utama, yaitu bersifat tegas dan dijalankan dengan kerangka waktu tertentu (fixed in time) seperti di Jepang 4 tahun, di India 5 tahun, dan di Mesir 7 tahun, dan lain sebagainya; lembaga pelaksananya sifatnya ad hoc, sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan; dan dikerjakan dengan cepat (rapid). Ketiga hal tadi, secara teknis dikerjakan oleh sebuah badan khusus yang mempunyai otoritas penuh menyelanggarakan RA yang bertugas untuk mengkoordinir semua sektor terkait, mempercepat proses pelaksanaan dan menangani konflik kepentingan yang kemungkinan besar terjadi. Tujuan utama RA adalah melakukan penataan kembali atau perombakan struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria (utamanya tanah) untuk kepentingan rakyat kecil, yaitu petani kecil, buruh tani, tunakisma dls, secara menyeluruh dan komprehensif (Russell King, 1977).
Karena itu terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang agar pelaksaan RA sesuai dengan tujuan yang dimaksud, yaitu memberikan tanah hanya pada mereka yang benar-benar mengerjakannya (penggarap), bukan pada yang “ongkang-ongkang kaki,” serta mengarusutamakan tanah sebagai fungsi sosial. Dengan demikian, tidak menjadikan tanah sebagai komoditas komersial, apalagi untuk kepentingan modal besar.
Secara teoritis, pelakasanaan RA di Indonesia dijalankan secara neo populis (bukan komunis atau kapitalis), meski Bung Karno sendiri kerap memakai istilah “sosialisme Indonesia.” Di mana tanah diredistribusi pada petani penggarap, bukan dikolektivisasi oleh negara seperti di negara-negara sosialis. Sedangkan secara historis RA tak bisa dipisahkan dari cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia (dekolonisasi) oleh para pendiri bangsa di masa awal kemerdakaan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, dan sejahtera bagi rakyat Indonesia dengan cara mengikis sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme. Maka, belumlah bisa dikatakan sebagai merdeka, meski mempunyai pemerintahan sendiri, oleh bangsa sendiri, sebelum terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Para pemimpin bangsa, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan telah memikirkan dan mencanangkan untuk merumuskan undang-undang agraria baru mengganti undang-undang agraria kolonial 1870. Disebabkan oleh kondisi politik yang belum stabil, pembentukan panitia agraria berlangsung silih berganti selama 12 tahun, mulai dari panitia agraria Yogya 1948; panitia agraria Jakarta 1952; panitia Suwahyo 1956; panitia Sunaryo 1958; dan rancangan Sujarwo 1960 (Wiradi, 2005: 27).
Di Indonesia RA sejati pernah dicoba untuk dilaksanakan pada tahun 1960 namun gagal oleh peristiwa Gestapu dan pergantian pemerintahan. Tidak hanya pelaksanannya yang belum usai, bahkan rancangan programnya pun, sebagaimana dikatakan Gunawan Wiradi, juga belum tuntas. Penjabaran UUPA 1960 yaitu UU No. 56/1960 yang dikenal sebagai land reform baru sebatas menyangkut pertanian rakyat. Sedangkan sektor-sektor lain seperti perkebunan, pertambangan, kelautan, kehutanan dll, belum sempat tergarap.
Salah Kaprah Kebijakan Agraria
Di masa reformasi, gagasan land reform muncul kembali di tahun 2001 dengan ditandai lahirnya TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keppres No. 34/2003 yang isinya memberi mandat kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk melakukan penyempurnaan terhadap UUPA 1960. Rancangan Undang-Undang (RUU) Agraria sebagai pelaksanaan Keppres No. 34/2003, ternyata bukan menyempurnakan tetapi malah mengubah UUPA 1960 (Wiradi, 2005: 32).
Sekarang di era pemerintahan Jokowi, RA mulai digulirkan kembali sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 45/ 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan disusul dengan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Fokus kebijakan agraria Jokowi adalah legalisasi dan redistribusi aset yang disebut Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 9 juta ha. Dari luasan tersebut, ditargetkan 4,5 juta ha untuk legalisasi aset yang terdiri dari 3,9 juta ha untuk sertifikasi tanah-tanah warga dan 0,6 juta ha untuk lahan transmigrasi. Sisanya seluas 4,5 juta ha dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta ha dari lahan HGU yang telah habis masa berlakunya dan yang diterlantarkan, dan 4,1 juta ha dari pelepasan kawasan hutan negara.
Bila tujuan minimalisnya untuk mengurangi konflik pertanahan yang angkanya tiap tahun terus meningkat, maka kebijakan agraria Jokowi telah gagal sejak dalam pikiran. RA diterjemahkan sebagai sebatas bagi-bagi sertifikat, pada tanah yang berstatus clean and clear. Sedangkan kita tahu, semua konflik tanah yang terjadi justru statusnya masih sengketa, umumnya antara petani penggarap/petani kecil dengan korporasi dan perhutani. Obral sertifikat juga bisa dibaca sebagai upaya memasukkan tanah bagi kepentingan modal besar, agar tanah lebih mudah dialihtangankan. Tak heran, berulangkali dalam berbagai kesempatan membagi sertifikat, presiden mengatakan bahwa tanah yang sudah dapat sertifikat bisa digunakan sebagai modal usaha.
Kalaupun dikatakan sebagai reform, maka kebijakan agraria Jokowi bukan dipimpin oleh negara, melainkan dipimpin oleh pasar (market led reform) yang menguntungkan korporasi. Beberapa dalil market led adalah menempatkan tanah sebagai komoditas, jual beli tanah harus bebas, dan legitimasi hak pemilikan harus diprioritaskan karena itu pembagian sertifikat diutamakan dan dibanggakan sebagai keberhasilan pelaksanaan RA.
Sedangkan mengenai tanah-tanah HGU, hingga kini datanya tak pernah dibuka oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan alasan melindungi pengusaha sawit, setelah Forest Watch Indonesia memenangkan gugatan di MA pada ATR/BPN untuk membuka data kepemilikan HGU. Sehingga wajar bila, penguasaan tanah secara luas seperti Prabowo maupun orang-orang dekat presiden tidak tersentuh oleh kebijakan agraria Jokowi. Selain dianggap legal, juga tidak masuk ke dalam TORA.
Memang HGU masih ada di dalam UUPA 1960, sebagai akibat dari kompromi politik Konferensi Meja Bundar. Namun Hatta, seperti di dalam pidatonya bulan Februari 1946, belum setahun Indonesia merdeka, mengingatkan bahwa perkebunan-perkebunan besar seharusnya di-RA kan sebab dulunya adalah milik rakyat yang diambil alih oleh perusahaan swasta.
Sedemikian, kebijakan agraria presiden Jokowi secara umum memunggungi semangat dan prinsip UUPA 1960. Bahkan di satu sisi mengatakan hendak mengikis ketimpangan agraria dan konflik agraria, namun di sisi lainnya kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah justru makin memperkeras konflik agraria di berbagai tempat di Indonesia, khususnya perampasan tanah untuk infrastruktur jaringan transportasi dan energi.
Dengan demikian, pernyataan Jokowi bahwa “dalam empat setengah tahun ini, hampir tidak terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur, karena tidak ada ganti rugi, yang ada adalah ganti untung,” tidak sesuai dengan kondisi kongkrit di lapangan dimana banyak masyarakat yang menolak pembangunan infrastruktur mendapatkan berbagai ancaman bahkan dikriminalisasi.
Penutup
Berdasar data historis dan kondisi kongkretnya, Indonesia dapat dikatakan belum memasuki transisi agraris. Meskipun industrialisasi sudah dimulai [meskipun juga gagal], tetapi belum pernah dilakukan RA secara tuntas yang semestinya dilangsungkan sebelum berlangsungnya proses industrialisasi, sebagai landasan pembangunan.
Sejak era Orde Baru hingga sekarang, fokus kebijakan agraria lebih memprioritaskan kepada upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal (investasi). Kebijakan yang dikeluarkan–telah dimulai sejak periode deregulasi kebijakan pertanahan (1980-an)–hanya difokuskan untuk memfasilitasi pemilik modal, baik asing maupun dalam negeri. Berbagai upaya deregulasi telah diciptakan untuk merangsang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sebab pemerintah berusaha menarik inverstor ke Indonesia, di mana pemilik modal dapat dengan cepat memperoleh tanah yang tak jauh beda dengan era Orde Baru. Di masa pemerintahan Orde Baru misalnya, kepala BPN Soni Harsono kala itu (1995) mengatakan bahwa“ untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka perlu ditempuh kebijakan deregulasi pelayanan di bidang pertanahan, sehingga proses pelayanan diharapkan dapat berlangsung secara lebih cepat, lebih murah tetapi tetap memberi jaminan kepastian hukum” (Ifdhal Kasim, 1996: 53).
Perjuangan Reforma Agraria haruslah ada di tangan rakyat yang berupaya mendongkraknya, yang kerap diistilahkan sebagai land reform by leverage. Dengan demikian, dibutuhkan kader-kader penggerak RA yang berbasis pada organisasi-organisasi tani lokal, utamanya para petani gurem, dan buruh tani tak bertanah untuk memperjuangkan terwujudnya RA sejati di Indonesia sebagaimana seharusnya.
Dengan tegas harus kita katakan bahwa kebijakan agraria Jokowi adalah reforma yang pura-pura (quasi-reform) atau reforma gadungan (pseudo-reform), yaitu suatu kebijakan yang seolah-olah melakukan pembaruan, tapi hakikatnya bukan pembaruan. Sedemikian kebijakan agraria Jokowi adalah pendomplengan terhadap terminologi RA. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kita semua untuk meluruskannya.****